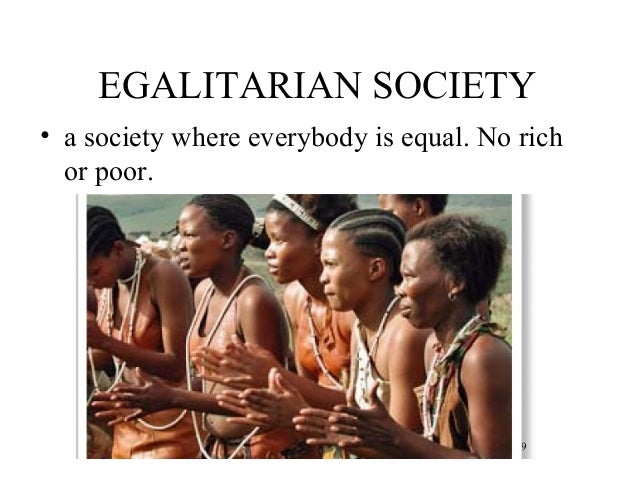Pelestarian Nilai untuk Pewarisan
Sejak pertama kali orang Batak menyadari dan menemukan dirinya sebagai bagian dari komunitas masyarakat modern, serentak itu pula ada gerakan yang muncul ke permukaan – entah tegas ataupun “malu-malu” untuk menjaga nilai-nilai kebatakan. Niatnya bagus: Di tengah gempuran modernitas berikut dampak mentalitas modern yang dibawanya serta, nilai-nilai kebatakan yang dipersepesikan dan di-aku-i sebagai nilai yang “luhur” harus dijaga sehingga bisa diwariskan ke generasi berikutnya.
Maka muncullah tagline–tagline populer yang secara masif “dijual”. Tak perduli jika marketer ‘brand’ Batak itu sendiri bahkan tidak tahu menggunakan bahasa Batak (entah Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Angkola atau Mandailing).
“Kalau bukan kita lagi yang menjaga nilai-nilai kebatakan ini, siapa lagi?” – Anonim
Tidak kurang juga apparel, kaos, motif, logo, ataupun niche–niche marketing lain yang didayagunakan untuk membuat seruan untuk pelestarian nilai-nilai kebatakan yang dimaksud. Harus diakui bahwa berkat promosi semacam ini, banyak orang yang berhasil mengorbitkan dirinya dan orang lain untuk tampil sebagai ‘duta Batak’, ‘ahli budaya Batak’, atau “akademisi Batak”. Tak perduli apakah para intelektual dan marketer ini pernah merasakan keriuhan dalam luapan emosi massa kala Mangalahat Horbo, Merdang-Merdem Kerja Tahun , Pesta Rondang Bittang dan sebagainya.
Silahkan tambahkan sendiri litaninya.
Batak diaspora yang tinggal di daerah dengan mayoritas penutur aktif berbahasa Inggris menggunakan ini untuk menegaskan akar budaya. Seakan berkata: Dear fellow brothers. I can fly to Paris, Rome, Birmingham, or wherever I want across the world, but I need you to know that my soul is really originated from somewhere else, far from here. It comes from my Bona Pasogit.

Image source: 2.bp.blogspot.com
Dengan semakin masifnya jumlah orang Batak yang merantau dan sudah dua atau tiga generasi tinggal di ibukota dengan budaya populernya, para marketer brand Batak ini pun merasa perlu membunyikan siapa itu Batak dengan bahasa Betawi.

Image source: 1.bp.blogspot.com
Tak terhitung juga usaha jual-beli memanfaatkan tagline “bangga jadi orang Batak” untuk memastikan bahwa mereka masih punya tempat di tengah-tengah persaingan harga dan kompetisi alur distribusi barang dan mode konvensional vs online shopping yang membuat wiraswastawan pemula sulit mendapat tempat.

Image source: 3.bp.blogspot.com
Jutaan gambar seperti ini bisa kita temukan di internet (dan akann terus bertambah setiap sepersekian detiknya), atau bahkan kaosnya sedang kita kenakan sembari membaca tulisan sederhana ini. Tidak ada maksud untuk menjustifikasi atau memberi ulasan etis terhadap promosi Batak yang tidak menggunakan ungkapan Batak ini. Kendatipun begitu, layak dicoba dan dianalisis kembali, jangan-jangan justru promosi terhadap “batak” atau “nilai-nilai batak” ini lebih maju jika seandainya berani menggunakan bahasa Batak sendiri. Misalnya, alih-alih “bangga jadi orang Batak”, tampilan “Bah … Halak Hita do Hape”.
Tetapi, pembahasan ini hanyalah lapisan kecil dari dinamika yang sebenarnya tadi: daya tarung nilai-nilai kebatakan di tengah zaman. Mereduksi nilai-nilai kebatakan hanya pada tampilan produk, tagline atau bahkan judul buku sekalipun adalah kesalahan yang mesti dihindari oleh siapapun yang berani menyebut diri sebagai “orang yang perduli dengan nilai-nilai kebatakan”.
Subtansinya bisa ditemukan pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sederhana ini:
“Mengapa orang Batak bangga mengenakan kaos bertema Batak?”;
“Kebanggaan apa yang dirasakan seseorang kala bertemu dengan orang lain yang ternyata sama-sama orang Batak?”
“Apa yang diharapkan oleh seorang batak ketika datang ke ‘punguan marga’ di tanah perantauan?”
Jika mengikuti nasihat Pramodya Ananta Toer yang mengajak kita untuk “berlaku adil sejak dalam fikiran”, maka jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sejenis itu akan menghantar kita pada refleksi NILAI – ideologi, kearifan, atau rekonsoliasi bersama orang Batak sepanjang sejarah keberadaannya.
Menggali Nilai dari Memoria
Setiap pewarisan selalu berarti “menghidupkan kembali” kenangan sangat kuat (memoria) yang menggetarkan dorongan bergemuruh dalam sikap hati (tremendum et fascinossum) agar aktif dalam bersikap dan bertindak dalam praksis hidup harian.
Mewariskan nilai-nilai kebatakan berarti aktif bergandengan tangan dan berbagi energi dalam proses transfer kuasa, dimana pewaris sebagai leluhur yang telah meninggal dunia, masih menguasai mereka semua ahli waris yang masih hidup (le mort saisit l’vif). Maka, warisan leluhur kita orang Batak harus bisa tampak nyata berbentuk peninggalan yang bernilai tinggi dan luhur mulia untuk diteruskan ke masa yang akan datang.
Dalam interpretasi orang Batak zaman sekarang, peninggalan itu – sayangnya – dianggap sudah utuh terpatri dan terkristalkan dengan membangun tugu marga semegah mungkin dengan biaya yang jumlahnya luar biasa.

Tugu Sitohang
Atau mengumpulkan dana untuk merenovasi makam leluhur sehingga tampak mentereng di antara pemukiman warga yang bahkan belum semuanya memiliki fasilitas MKC.

Bahkan di area perladangan, bangunan semegah ini bisa mudah ditemukan
Pertanyaan yang relevan ditanyakan ialah:
Warisan apakah dari leluhur kita moyang Batak, yang bernilai luhur tinggi dan benar-benar baik serta bermanfaat untuk diteruskan bagi generasi kini dan yang akan datang?
Perspektif Humanis: Belajar dari Sejarah
Nikolas Simanjuntak menerangkan dengan cukup lengkap perihal nilai-nilai yang ada dan patut diwariskan berikut self-positioning yang mesti diambil bagi orang Batak yang saat ini menjadi ahli warisnya, yakni “menatap ke depan dengan memposisikan masa lalu sebagai bahan yang sungguh amat penting bagi pembelajaran di masa akan datang”. Menanggalkan masa lalu yang tidak bernilai untuk masa depan, memaafkan segala yang kita nilai kini sebagai kesalahan dan kekeliruan di masa lalu (forgive but not to forget).
Hal ini persis sejalan dengan nilai tradisi asli Batak:
“Sude do hinauli na denggan na burju ingkon siingoton, alai sude sahit dohot jea ingkon do bolongkonon”.
Sekali lagi, Mengupas Nilai dengan Demitologisasi
Dengan begitu, warisan yang bisa kita petik dari narasi folklore ‘sejarah Batak’, mulai dari mitos penciptaan di yang bernilai kultural tradisional khas Batak alami (natural particularity), hanya bisa dirunut dari upaya tafsir modern terhadap narasi kisah tersebar yang telah umum diketahui saat ini. Upaya menafsirkan itu berarti juga cara merasionalkan segala mitos, atau demitologisasi, narasi ‘sejarah Batak’ agar generasi terkini dapat memperoleh manfaat pemahaman rasional dari nilai kultural tradisional khas Batak (cultural identity), seraya menaruh rasa hormat kepada si penutur kisah.
Tafsir apakah yang bisa dipetik dari narasi kisah itu sebagai folklore yang bernilai luhur tinggi untuk masa kini dan ke depan?
Sekurang-kurangnya ada 7 (tujuh) butir berikut ini, yang dapat disebut untuk dikembangkan lagi secara kreatif-inovatif bagi kemaslahatan bersama Batak modern generasi kini.
Pertama, sikap hormat sepenuhnya kepada orang tua yang masih hidup dan yang sudah meninggal, terutama hormat bagi nenek moyang orang tua dan semua anak turunannya. Urutan asal pohon silsilah yang jelas, harus terus dicatat untuk dipelihara dan diturunkan ke putra-putrinya. Karena tanpa itu, bisa jadi timbul masalah serius, jadi tercerabut dari akar pohon asal-usul budaya keluarganya sehingga disindir sebagai Dalle [mengaku diri Batak tapi tak paham tentang Batak]. Kendatipun sebutan dalle ini umumnya dengan nada arogan dilontarkan oleh orang Batak Toba yang merasa harus menjadi pusat dari “bangso Batak”.

Entah dia Ph.D dari Harvard ataupun presiden direktur di perusahaan blue chip, setiap orang Batak akan patuh pada “hata ni dainong”
Kedua, Kearifan lokal Batak dengan identitas kultur yang partikular unik dan bernilai luhur tinggi. Terutama ini bisa ditemukan sebagai Dalihan Na Tolu, local genius dalam sistem relasi religi sosial demokratis:
Somba marhula-hula – Manat mardongan tubu – Elek marboru.
Hula-hula (pihak marga isteri, ibu sendiri, ibu ayah) di setiap keluarga Batak dan semua saudaranya, hingga kini masih sangat dihormati (somba). Begitu juga semua keluarga hula-hula selalu dengan penuh kasih (elek) kepada Anakboru yang menghormatinya selaku Hula-hula. Diantara sesama dongan tubu (sesama keluarga semarga sendiri), harus selalu saling super hati-hati (manat-manat) penuh pertimbangan akal sehat dalam setiap relasi, agar jangan pernah sampai timbul selisih paham jadi masalah yang serius. Dengan demikian, riset atau observasi yang jujur terhadap praksis harian kehidupan orang Batak niscaya akan membawa orang sampai pada hipotesa ini:
Demokrasi yang egaliter, transparan, dan akuntabel, sudah berakar dalam praktik kultur asli Batak, bukan lagi sekadar konsep.
Image source: Adam Carter via Slideshare
Ketiga, Kepribadian pekerja keras berkarakter ulet, berdaya-tahan, tak kenal menyerah, sampai mampu mempertahankan diri dan seluruh keluarganya dari segala ancaman marabahaya fisik dan non-fisik untuk hidup berlanjut (sustainable survival). Karakter ini sudah dikenal luas oleh masyarakat nusantara, sebagai Batak yang keras, tegas, eksplosif, ulet, pekerja yang rajin, dan seterusnya Tapi sering juga salah tingkah, karena jadi tampak garang, sangar, tanpa basa-basi diplomasi, hingga bahkan bisa jadi diberi cap kasar (stereotype). Tampilan kemasan luar “tampak kasar” ini harus diperbaiki terus-menerus oleh generasi Batak era modern kini dan ke depan. Namun, jangan sampai menghilangkan mentalitas jatidiri kepribadian berkarakter yang sudah terpatri dan dikenal umum selama ini.

Image source: Aureusanalytics.com
Keempat, daya mampu spiritualitas dan komunikasi batin yang sangat kuat dan mendalam, menyatu-padukan kekuatan metafisis alam semesta (holistic resources spirit) sebagai dasar hidup rohani dengan terus mengasah olah-batin mondar-mandir ke daya olah-pikir.
Pastilah, setiap moyang Batak yang hidup di isolasi alam ganas itu memiliki kekuatan fisik dan spiritual yang hebat dan mengagumkan. Mereka berani mengarungi ganasnya alam dan hewan air di sekitar danau Toba dalam situasi geografi tahun 1300-1800an.
Dari daerah Balige di arah timur, ada yang bertualang ke ujung paling barat danau di kaki pegunungan seram di pinggiran hutan lebat, hunian gajah dan harimau sumatra yang terkenal ganas di huta Sihotang. Dan setelah memperoleh isteri dari keluarga Raja Sihotang, maka pastilah Raja ini tidak asal sembarang marhela kepada seorang Raja juga yang memperisteri putrinya. Raja Sihotang adalah jagoan dalam fisik dan non-fisik.
Leluhur Batak lain yang bahkan melintasi ialah Ompu Jelak Maribur. Jika Raja Sihotang hanya diwarisi keleluhurannya oleh orang Batak Toba, Ompu Jelak Maribur diakui oleh beberapa sub-suku Batak sekaligus. Marga Dalimunthe di Tapanuli Selatan mengakuinya menurunkan leluhur mereka, marga Haromunthe dari Sibabiat mengagumi kepiawaian “ompung” mereka menggunakan ultop, bertualang hingga ke Dolok Sanggul dan menyatukan marga Munthe Dolok Sanggul dan diyakini juga menurunkan zuriatnya pada marga Munthe yang ada di Simalungun.
“Rap halak jolma na gogo di parbadanon nang di partondion”, inilah ungkapan yang patut dialamatkan kepada kedua tokoh leluhur ini.
Kedua tokoh ini hanya contoh. Kelompok genealogi Batak lain juga umumnya memiliki versi heroisme leluhur yang mereka saling bagikan sebagai folkore pembentuk raison d’etre dari masing-masing “punguan”.
Para tokoh ini umumnya digambarkan begitu hebat dan mengagumkan dengan kekuatan fisik dan daya spiritual sangat tinggi. Selama bertahun berbilang bulan mereka berjalan kaki menjelajah hutan rimba raya pegunungan dingin menggigit, saban hari diintai hewan buas, dan mendayung di perairan dengan segala ancaman bahaya arus dan angin. Mereka tidak pernah alpa memberi tempat bagi providentia divina a la Batak dalam setiap kesulitan hidup mereka. Mereka memohonkan tonggo-tonggo kepada Debata Mulajadi Nabolon, Tuhan asli orang Batak. Seperti yang dilakukan oleh Jelak Maribur dalam situasi batas ketika dia harus menghadapi penghakiman dari saudara-saudaranya sesama keturuan Nai Ambaton, tetapi lalu terharu melihat perspektif humanis dari hula-hula-nya Tamba Lumban Tonga-tonga yang melampaui tradisi demi nilai sejati dari hidup manusia. Dia diselamatkan dari kekejian tradisi yang terbelenggu dogma sesuai konteks saat itu. (Menurut aturan saat itu, kesalahan yang dilakukan dengan mengawini boru Lumban Tonga-tonga adalah pelanggaran serius yang layak diganjari hukuman mati).

Marga Tamba Lumban Tonga-tonga menyelamatkan Ompu Jelak Maribur dari ‘human sacrifice’ seperti pada adegan Apocalypto ini.
Terbukti pula, kini di era modern, kita ketahui bahwa laju sejarah kemajuan perkembangan hidup beragama dan berpendidikan yang terjadi di tanah Batak ternyata dicatat sebagai salah satu “yang tercepat lajunya” dari berbagai belahan dunia lainnya.
Kelima, ‘sense of community’ yang punya landasan kuat pada urutan generasi penomoran pohon silsilah keluarga setiap marga yang relatif kecil kekeliruannya. Hal ini bisa difahami mengingat kuatnya identitas khas sistem relasi Dalihan Na Tolu. Selain itu, kekeliruan bisa jadi soal yang serius seperti sindiran Dalle. Itu bisa terjadi sebagai keterputusan budaya (diskontinuitas), karena ‘praktik lalai’ atas berbagai sebab dan alasan menghilangkan keunikan tradisi dan identitas khas Batak dalam diri dan keluarga intinya disebabkan situasi lokal perantauan.

Situasi diskontinuitas ini nyata sangat rawan bagi generasi Batak modern terkini, yang bisa jadi punah pada dua-tiga generasi dari sekarang. Sebab, relasi emosional generasi perkotaan sudah tidak tersambung dengan generasi di tempat asal (bona pasogit), terutama setelah generasi orangtua masing-masing sudah meninggal dunia. Tambahan lagi, bahasa Batak dan acara-acara budaya asli sudah tidak menarik perhatian generasi terkini, karena dianggap memboroskan energi, waktu, dan biaya.
Keenam, Pesan yang jelas bahwa segala bentuk kekerasan dan “permusuhan antar keluarga” di dalam nuansa dan nada kisah narasi beberapa marga Batak, harus ditinggalkan semua aspek kekerasannya. Tafsir teks dan konteks harus dilakukan terhadap situasi faktual sosio-geografi di era tahun 1300-500an, yang tidak/belum kenal budaya baca-tulis, untuk mencatat fakta laporan peristiwanya. Namun, benarlah keberlanjutan hidup diri sendiri dan keluarga di dalam kisah folklore itu, hanya bisa diteruskan oleh yang terkuat mampu bertahan (survival for the fittest) sebagai nilai ajaran.
Tak pernah bisa dibenarkan adanya nilai luhur yang rasional dari “permusuhan antar saudara” untuk boleh diwariskan. Kecuali jika hal yang diwariskan adalah: jangan pernah ada permusuhan lagi antar sesama semarga kapan dan dimana pun. “Ia molo dung sega, dipauli ma, alai molo adong ia na tading, niulahan mamukka paulihon.” Ini pun local genius Batak juga.
Cukup melegakan melihat bahwa dalam beberapa perbincangan di dunia nyata maupun dunia maya, semakin banyak orang yang meng-edukasi diri untuk melihat setiap teks mitos dalam konteksnya. Semakin banyak yang menyadari bahwa toleransi antar rumpun marga menjadi penting, mengingat bahwa pemangku marga-lah yang paling otoritatif menjadi pembicara dari identitas mereka, bukan orang lain di luar rumpun marga tersebut (kendatipun hal ini kerap diracuni juga oleh sikap kampungan yang tidak menerima pendapat lebih fair dari “sibottar mata” yang malah lebih menguasai literasi dan dokumentasi historis Batak). Semakin banyak yang merasa perlu membela jika seorang Batak di-bully dan disebut “dalle” oleh pihak lain, yang menjadi pembaca buta terhadap folklore dari inner circle-nya tanpa pernah keluar dan menerima versi lain yang lebih multi-displin.

Pembaca tarombo buta biasanya menjadi “physicologically sick” karena kerap terlalu arogan, hingga menghakimi orang Batak lain sebagai dalle berdasarkan parameter yang dibuat oleh kelompoknya sendiri, lebih sering menutup diri terhadap riset-riset ilmiah terbaru tentang tema relevan.
Ketujuh, warisan nilai tradisional kultural Batak yang bernilai luhur tinggi bagi generasi terkini, yaitu: agar kita senantiasa saling merawat kasih kemanusiaan dan melestarikan sikap anti-segala kekerasan (nonviolence).
kisah seram “permusuhan antar saudara” di dalam satu marga, telah menjadi luka batin mendalam menusuk tulang sumsum secara berantai bergenerasi dengan semua akibat ikutannya dialami hingga ke masa kini. Luka-luka batin itu dikisahkan, konon terjadi di masa lalu, di sekitar tahun 1300-1500an. Bagi generasi sekarang, dengan segala kemajuan akses informasi, kearifan hendaknya menuntun orang pada sikap untuk memafkan, walau tak perlu melupakan pembelajaran bernas yang bisa dipetik darinya.
Biarlah itu tinggal, jadi masa lalu untuk dimaafkan.
Maka, jangan pernah diulangi lagi sampai kapan, dimana pun, dan oleh siapa pun juga.
Jangan pernah lagi semarga dibunuh melalui persekongkolan demi perebutan tanah warisan orang tua. Jangan pernah lagi seorang diadili tanpa mengindahkan praduga tak bersalah. Jangan pernah lagi menggunakan dalih ‘punguan’ untuk mem-vonis orang lain bahkan keturunannya sebagai “pantas dimusnahkan”.
Luka lama “permusuhan antar saudara” bisa juga terjadi antar saudara satu Ayah dari dua/lebih ibu. Maka, jelas dan tegas jadi moral warisan yang diturunkan dari narasi Folklore ini adalah: Lelaki Batak jangan pernah berpoligami, “marimbang” atau “unang mardua-dua inanta di jabu”.
Sebuah lirik dalam tonggo-tonggo memuat pesan moral kaya ini
“Si dangka ni arirang, arirang ni Pulo Batu;
Na so tupa sirang naung ho saut di ahu;
Na so tupa marimbang sai hot tondi di jabu.”
Tugas Penting Berikutnya
Menjelaskan dan memahami secara komprehensif, benar, dan baik tentang esensi kisah narasi dan luka-luka batin itu, memang juga sungguh sulit dicarikan obatnya di masa lalu. Pastilah, itu karena informasi pengetahuan, ilmu, dan teknologi terbatas di masa itu. Sulit cari obat, juga kita temukan dalam pengalaman banyak penyakit di masa lalu. Tapi di zaman ini, sudah hampir tiada penyakit yang tak bisa disembuhkan. Luka batin permusuhan ini, jika pun tak bisa kita sembuhkan, tapi bisa kita tanggalkan. Kita tinggalkan masa lalu, seraya menatap hari esok dan ke depan.
“Sae ma angka na salpu, lupa ma angka na tading gabe ilu-ilu, sai ro ma angka na uli na denggan, martua dapotan sude gabe pasu-pasu, marsogot nang haduan.”
Satu hal jelas: Segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan permusuhan itu adalah nyata menjadi pelanggaran HAM (hak-hak asasi manusia), yang dilarang oleh sistem budaya dan hukum negara. Hal ini juga jelas dan tegas dilarang oleh sistem dunia internasional. Oleh sebab itu, tidak mungkin diteruskan sebagai warisan yang bernilai bagi generasi kini dan yang akan datang. Suara yang mengatakan bahwa pemusnahan kehidupan manusia lain adalah nilai indigenous Batak, suara semacam itu adalah suara sumbang. Yang menyuarakannya, entah tidak belajar dari narasi folkore, hanya sekedar membaca “tarombo” secara buta, atau sengaja menipu untuk menegaskan kekuasaan yang dimilikinya untuk menindas orang lain.
Bersama dengan agama, kelompok, aliran ideologi, dan lokalitas, kesatuan dalam berbagi tarombo yang sama adalah anasir-anasir pembentuk sense of community (rasa berkomunitas), hal yang tentunya dicari oleh siapapun untuk mengisi aspek sosiologis dari kodrat individu yang secara paradoks masing-masing egois. Kita menemukan luapan kegembiraan dan kehidupan ketika bersama dengan orang lain. Entah itu bersama-sama melakukan ritual atau ajaran agama kita, bersama merayakan kemenangan tim sepakbola favorit kita, bersukaria ketika ideologi kita diterapkan di komunitas masyarakat tempat kita tinggal, atau sekedar memiliki alasan untuk lebih cepat dekat secara emosional dengan orang yang baru kita temui hanya karena dia satu marga, satu bahasa atau satu tarombo dengan kita: “Horas bo, ai sarupa do hape oppungta“.
Akan tetapi, tentu saja semua itu adalah instrumen yang membantu kita untuk mencapai kemanusiaan yang lebih utuh lagi. Jika salah meletakkan prioritas, bisa-bisa kita mendapati diri kita sedang meng-kafir-kan atau menganggap sesat ajaran agama orang lain yang tak seagama dengan kita, tawuran dan aksi saling lempar dengan suporter dari klub sepakbola lawan tanding klub kita, menghalalkan segala cara termasuk menindas dan menyogok pemerintah untuk memenuhi hasrat ideologi kita, atau secara terang-terangan menghindari orang yang berbuat baik kepada kita hanya karena kita memiliki tarombo yang berbeda. Alih-alih memperkaya kemanusiaan kita, atas nama pemuasan hasrat sense of community (kerinduan untuk berada dalam kumpulan yang sama dengan sebanyak mungkin orang), kita malah menindas sesama manusia yang lain. Nilai pelestarian hidup kita tinggalkan, euforia dan riuh-rendah serta gegap-gempita pesta kelompok kita agungkan.
Jika kita tidak mawas diri, kesalahan meletakkan prioritas (skala nilai) ini akan menjadi kebiasaan. Begitu menjadi kebiasaan, kita tidak sadar lagi bahwa kita sedang melakukan kesalahan. Tanpa kesadaran akan kesalahan meletakkan prioritas, kita akan semakin dekat ke chauvinisme radikal dan fanatisme kelompok yang sempit. Hal-hal ini adalah jelas-jelas virus yang membawa penyakit kemanusiaan. Jika kita tidak rajin-rajin melatih kesadaran kita (examen conscientiae) terhadap nilai tertinggi dari hidup kemanusiaan kita, maka kita menjadi agen sukarela yang mengembang-biakkan virus-virus penyakit kemanusiaan tadi. Kita menjadi manusia pesakitan. Untuk penyakit semacam itu, hanya ada satu solusinya:
“Ai sahit sisongon i, nang sude angka jea na sotupa, ingkon do i hatop-hatop bolongkonon.”